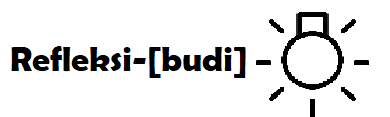Franz Rosenthal, seorang orientalis terkenal, menulis bahwa sebuah peradaban memiliki kecenderungan untuk berpusat pada satu konsep tertentu, dibandingkan dengan konsep-konsep lainnya, yang kemudian memberikan karakter khas bagi peradaban itu. Dalam peradaban Islam, konsep itu adalah konsep ‘ilmu. Konsep ilmu inilah yang mendominasi dan mencirikan peradaban Islam (dalam manifestasi klasiknya) [KT, 1-2]. Dia juga mengungkapkan, “Sebuah peradaban muslim tanpa pengetahuan tidaklah terbayangkan oleh generasi muslim pertengahan.” Seorang futurulog Muslim, Ziaudin Sardar, bahkan mengatakan sebenarnya peradaban muslim klasik yang tinggi itu secara keseluruhan ruhnya adalah pengetahuan, dengan mencari, menguasai, membangun institusi untuk menyebarluaskan, menuliskan, membaca, menyusun serta menumbuhsuburkan pengetahuan itu.
Konsep Ilmu
Dengan merujuk kepada Al Qur’an sebagai sumber Islam kita menemukan betapa pentingnya konsep ilmu dan peranannya dalam Islam. Salah satu indikasi dari penekanan atas konsep ilmu ini dalam Al Qur’an adalah perulangan penggunaan konsep-konsep itu dalam beragam variasi semantiknya. Ilmu merupakan kata ketiga yang menempati tabulasi frekuensi terbesar dalam Al Qur’an setelah kata Allah dan Rabb. Konsep-konsep penting lain dalam pandangan dunia Islam, semisal keadilan (‘adl), juga memiliki frekuensi penggunaan yang besar (melalui beragam variasi kata maupun sinonim dan antonimnya). Besarnya frekuensi ini merupakan salah satu indikasi, walaupun bukan satu-satunya indikasi pentingnya konsep ini dalam pandangan dunia Islam. Hal ini perlu ditegaskan karena kita juga dapat menemukan satu konsep yang hanya digunakan dua kali, kata syura (musyawarah), yang memiliki arti besar dalam politik Islam [KP, 34-35].
‘Ilm berakar pada kata ‘alamah yang berarti tanda, simbol atau lambang, yang dengannya seseorang atau sesuatu dikenal. Sumber pengetahuan dalam konsep Islam adalah Tuhan, karena Dia-lah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ilmu terkait dengan kebenaran (al haq) dan kepastian (al yaqin), sebagai anti-tesis dari kesalahan (al bathil), keraguan (al syakk) dan dugaan (al zhann). Ilmu dalam Islam juga memiliki sifat yang holistik, yang merupakan refleksi dari konsep tauhid yang mendasar. Wahyu sebagai tanda-tanda (ayat-ayat) Tuhan yang tertulis, menegaskan kecocokannya dengan ayat-ayat Tuhan yang lain dalam alam, sejarah maupun psikologi manusia itu sendiri. [KP 66, 67,70].
Secara logis pengetahuan harus diikuti oleh perbuatan yang baik. Pengetahuan juga memiliki signifikansi bagi perkembangan spiritual pribadi Islam yang benar. Mereka yang memiliki pengetahuan, yang mampu menjaganya dari perbuatan yang salah dan mendorongnya melakukan tindakan yang benar disebut sebagai mereka yang memiliki hikmah. [KP 71, 78]
Pengetahuan memiliki sifat yang tak terbatas. Al Quran menggambarkan bahwa di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui (12:76). Oleh karenanya kita diperintahkan untuk mencari pengetahuan lebih banyak, sebagaimana Musa mencari pengetahuan dari seorang hamba Allah yang darinya ia menggali banyak hikmah. Sebagaimana juga Nabi Muhammad diperintahkan untuk selalu berdoa agar ditambahkan ilmu (20:114). [KP :114]
Konsep pengetahuan, akan lebih jelas dengan melihat pula kebalikannya maupun memahami sinonimnya. Medan semantik pengetahuan (dalam Al Qur’an) juga memasukkan di dalamnya konsep-konsep sinonimnya; sebagai contoh proses dan hasil perenungan (tafakkur dan tadabbur), pemahaman (fiqh), petunjuk spiritual (huda) dan cahaya (nur), kebenaran (haq), keyakinan (yaqin), dan iman dan taqwa. Antitesis pengetahuan adalah tidak mengetahui (la ya’alamun), tanpa pengetahuan (bighairi ‘ilm), subhah (skeptis), syakk (ragu), raib (ragu, curiga), zhann(dugaan), hawa (keinginan), bathil (salah), zhulman (kegelapan) dan jahl (kebodohan). Para ulama klasik memahami jahl sebagai lawan langsung dari ‘ilm. (Sementara beberapa orientalis, berdasarkan analisis semantik, memahami jahl sebagai lawan kata hilm (kesantunan)). [KP:79,82]
Hadist sebagai sumber kedua agama Islam juga dapat dirujuk guna memahami signifikansi ilmu dalam peradaban Islam. Kumpulan beragam kodifikasi Hadist banyak mengklasifikasikan hadist-hadist dalam bab-bab terkait dengan ilmu, belajar maupun mengajar. Salah satu hadist yang bisa dikutipkan sebagai ilustrasi mengenai pentingnya ilmu adalah salah satu sabda Rasulullah yang menyatakan keunggulan seorang berilmu dibandingkan dengan orang yang beribadah seperti terangnya bulan purnama dan bintang-bintang. Kitab Sahih Bukhari, maupun Sahih Muslim memulai dalam bagian-bagian awal mereka dengan bab maupun kitab mengenai ilmu. Peran penting ilmu diungkapkan secara ringkas oleh Imam Bukhari melalui ungkapan, “Ilmu mendahului amal”, yang menjadi salah satu judul bab dalam sahihnya.
Buku-buku klasik Islam banyak juga memulai pembahasan mereka dengan bab mengenai ilmu, sebagai contoh kitab klasik Ihya Ulumiddin karangan Iman Ghazali. Berikut kita kutip kata-kata bijak Al Ghazali untuk mengilustrasikan pentingnya ilmu dalam kehidupan, “Orang-orang yang selalu belajar akan sangat dihormati dan semua kekuatan yang tidak dilandasi pengetahuan akan runtuh.”
Ulama-ulama kontemporer di zaman ini juga memiliki perspektif yang sama. Yusuf Qaradawi misalnya, ketika membahas seri pembahasannya mengenai kehidupan ruhaniah seorang muslim memulainya dengan pembahasan mengenai urgensi menegakkan kehidupan ruhaniah (nuansa robbaniyah) di atas landasan ilmiah. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa ilmu merupakan pembuka jalan bagi kehidupan spiritual yang terbimbing, ilmu merupakan petunjuk iman, penuntun amal; ilmu juga yang membimbing keyakinan dan cinta. Dalam risalahnya mengenai prioritas masa depan gerakan Islam, beliau menempatkan prioritas sisi intelektual dan pengetahuan melalui pengembangan fiqh baru sebagai prioritas awal.
Budaya Ilmu
Budaya Ilmu ialah wujudnya keadaan dimana setiap lapisan masyarakat melibatkan diri, baik langsung atau tidak, dalam kegiatan keilmuan dalam setiap kesempatan [BI 29]. Ia juga merujuk pada wujudnya satu keadaan dimana setiap tindakan manusia, baik pada skala individu maupun masyarakat diputuskan dan dilaksanakan berdasarkan ilmu. Dalam budaya ini, ilmu merupakan keutamaan tertinggi dalam nilai pribadi maupun masyarakat; individu dan masyarakat terlibat dalam memberi bantuan, kemudahan dan pengakuan yang tinggi terhadap individu maupun lembaga yang terlibat dalam pencarian dan penyebaran pengetahuan. Masyarakat berbudaya ilmu juga menilai negatif terhadap sifat jahil, bebal dan anti-ilmu. [BI 29]
Pentingnya budaya ilmu ini bagi sebuah peradaban adalah karena ia merupakan syarat bagi kejayaan dan kekuatannya. Bangsa yang kuat (secara fisik-material) tanpa ditunjang budaya ilmu yang baik akan terserap oleh peradaban lain yang lebih baik budaya ilmunya. Dari sejarah kita memahami bagaimana suku Jerman yang menaklukan imperium Romawi di abad ke-4, justru terserap ke dalam budaya Romawi, demikian pula pasukan Mongol yang terserap ke dalam peradaban Islam maupun Cina yang lebih kuat budaya ilmu-nya. [BI 11-12]
Dalam abad modern ini, dimana renaisans atau kebangkitan kembali umat banyak didengungkan, pembinaan budaya ilmu merupakan keharusan. Sebagaimana diingatkan oleh Anwar Ibrahim bahwa proses membangkitkan umat sangat terkait dengan upaya pengembalian posisi sentral pengetahuan dan pendidikan dalam masyarakat dengan memperkuat api semangat belajar dan mendorongnya untuk tertarik pada ladzzah al ma’rifah (kelezatan pengetahuan), kenikmatan berjumpa dengan pikiran-pikiran besar, dan ketakjupan dalam menemukan gagasan-gagasan baru. Membangun keutamaan budaya sebuah masyarakat merupakan kerja pemberdayaan aksara (literary empowerment) terhadap mereka. Anwar Ibrahim juga mengingatkan akan permasalahan yang masih dialami sebagian besar dari umat ini, “Kita bangga dengan Islam sebagai agama yang banyak berbicara mengenai ilmu. Kata pertama yang pertama diturunkan dalam Quran adalah iqra’. Tetapi kita melihat kini sebagian besar muslim tidak dapat membaca. Sebagian yang bisa membaca tetapi tidak memahami. Mereka yang bisa membaca dan memahami sebagian terjebak pada buta huruf budaya (culturally illiterate). Salah satu fenomena buta huruf budaya ini terlihat pada sikap filistinisme, perhatian terhadap soal-soal dan kebiasaan yang remeh”.
Imam Ghazali dan Budaya Ilmu
Imam Ghazali dalam upayanya membangkitkan ilmu-ilmu agama (ihya ‘ulumi-ddiin) memulai-nya dengan menulis buku pertama dengan buku mengenai ilmu (Kitabul ‘Ilm). Dari buku ini kita bisa memahami bagaimana konsep dan budaya ilmu direpresentasikan dalam peradaban Islam klasik.
Kitab Ilmu ini dimulai dengan bab mengenai Keutamaan Ilmu serta Keutamaan Belajar dan Mengajar. Melalui kutipan-kutipan dari Al Qur’an, Hadist maupun ucapan-ucapan penuh hikmah dari tokoh-tokoh pendahulu Imam Ghazali mengungkapkan keutamaan tiga aspek mendasar ilmu di atas; ilmu itu sendiri, belajar dan mengajarkannya. Demikian pula beliau mengutarakan argumentasi rasional atas keutamaan ilmu. Menurut beliau keutamaan sesuatu muncul jika ada bandingannya dengan yang lain seperti keutamaan kuda atas keledai, karena faktor kecepatannya walaupun memiliki kesamaan dalam kemampuannya memikul beban. Ilmu merupakan keutamaan pada dirinya, secara mutlak, tanpa kaitan (bandingan) dengan yang lain. Beliau juga mengungkapkan, sesuatu itu berharga dan diminati terbagi dalam tiga kategori (1) diminati sebagai sarana memperolah yang lain (2) diminati karena dirinya sendiri (3) diminati karena dirinya sendiri sekaligus sebagai sarana memperoleh yang lain. Ilmu diminati karena dirinya sendiri sekaligus sarana untuk memperoleh yang lain.
Selanjutnya beliau menerangkan mengenai klasifikasi ilmu yang fardhu ‘ain dan fardhu kifayah. Mengenai ilmu yang terpuji dan tercela, serta keutamaan ilmu-ilmu akhirat (ilmu mu’amalah-dalam arti etis). Kenapa ilmu perlu dibagi, berdasarkan kewajiban pencariannya, menjadi fadhu ‘ain dan fardhu kifayah ? Ini terkait dengan skala prioritas. Ilmu yang berperan dalam keselamatan pribadi dunia dan akhirat harus dituntut dalam prioritas pertama. Ilmu yang terkait dengan kemaslahatan bersama bersifat distributif bagi anggota masyarakat. Dengan konsep ini juga kita menyadari tidak semua ilmu harus kita kuasai, dengan alasan sederhana, ilmu begitu luas sedangkan umur kita cukup pendek.
Setelah membahas mengenai kerancuan makna yang muncul di zamannya terkait dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh setiap orang, serta pembahasannya mengenai ilmu debat; beliau membahas mengenai adab belajar dan mengajar. Selanjutnya membahas berbagai penyakit terkait ilmu dan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama busuk. Ini merupakan pembahasan mengenai tanggung jawab ilmiah bagi seseorang maupun etika ilmiah.
Pada akhirnya buku ini diakhiri dengan pembahasan mengenai akal, hakikat dan pengertiannya serta perbedaan tingkat manusia sesuai dengan akalnya.
Bebalisme dan Sikap Anti-Ilmu
Tentu saja lawan ilmu adalah kebodohan. Kebodohan bisa pada tingkat sederhana, karena memang ketidaktahuan objektif seseorang, atau pada tingkat kedua karena sudah mengira tahu tetapi hakikatnya dia tidak tahu, sehingga menghalanginya untuk belajar lebih lanjut (jahil murokkab). Syed Husein Alatas mengembangkan konsep “bebalisme” secara sosiologis untuk menggambarkan fenomena kejahilan murakkab (berganda) ini dan implikasi sosiologisnya dalam masyarakat. Bebalisme merupakan sikap yang termanifestasi dalam ketidaktahuan, lamban, acuh dan keras kepala.
Orang bebal, menurut beliau, tidak memiliki daya antisipasi terhadap masalah, hanya bereaksi setelah sebuah peristiwa terjadi. Bebalisme membuat orang tidak kreatif dan tidak orisinal. Orang bebal tidak mengembangkan rasionalitas substansial, yang mau menelisik dan mengungkap wawasan-wawasan atas peristiwa; dia juga tidak mengembangkan rasionalitas fungsional, yang muncul sebagai sebuah tindakan yang mengacu pada sasaran tertentu. Bebalisme membuat orang kurang hasrat untuk melakukan pengkajian secara ilmiah, tidak memiliki kecintaan terhadap argumentasi yang tertib dan rasional. Bebalisme menghalangi kecintaan kepada ilmu. Menggejalanya sikap bebalisme dapat menumbuhkan kebiasaan, tradisi atau budaya anti-ilmu, anti-pembahasan, anti-penalaran dalam sebuah masyarakat.
Aktivis cum Intelektual
Menjadi aktivis identik menjadi man of action, manusia yang banyak bekerja alih-alih banyak berpikir. Mereka yang terlibat dalam upaya memberdayakan masyarakat (melalui dakwah dan pendidikan) biasanya banyak terserap pada beragam aksi, yang kadang membuatnya menjadi sangat sibuk. Kultur kesibukan dalam aksi kadangkala membuat seseorang enggan untuk meluangkan waktu untuk berpikir mendalam (berikut aktivitas turunannya secara operasional, mulai dari diskusi, evaluasi hingga perencanaan matang). Sikap “yang penting beramal” jika tidak ditempatkan dalam proporsi yang sesuai dapat mereduksi pentingnya semangat pencairan ilmu dan merangsang orang untuk menolak hasil pemikiran, ilmu maupun keengganan untuk meneliti dan berpikir secara mendalam.
Membaca
Budaya ilmu sangat terkait dengan budaya membaca. Membaca selain merupakan salah satu sarana untuk menggapai ilmu, pada dirinya sendiri membaca merupakan sebentuk kenikmatan, juga sebuah sarana rihlah guna menjelajah dunia pemikiran. Menurut satu keterangan, membaca dalam bahasa arab (qara-a) diartikan sebagai menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-cirinya dan sebagainya, yang kesemuanya dapat dikembalikan kepada hakikat “menghimpun” yang merupakan arti akar kata tersebut.
Kalau aktivitas membaca merupakan aktivitas menghimpun, kemudian apa yang dihimpun ? Tentu saja pengetahuan. Lalu apakah pengetahuan itu ? Pada bagian di atas kita sudah mengenal konsep ilmu dalam Islam, tetapi belum diungkapkan definisi dari ilmu. Mengacu pada apa yang disampaikan oleh Syed Naguib Al Attas, ilmu bisa diartikan sebagai tibanya jiwa pada makna sesuatu [objek pengetahuan itu] atau sebaliknya dari perspektif yang berbeda, ilmu adalah kedatangan makna pada jiwa. Apa itu makna ? Makna merupakan pengenalan tempat-tempat sesuatu dalam suatu sistem. Dengan demikian sasaran sejati dari proses pembacaan adalah terhimpunnya pengetahuan dalam diri kita, pengetahuan yang memberi makna kepada jiwa kita.
Mungkinkah membaca atau banyak membaca tidak memberikan pengaruh pada terhimpunnya pengetahuan secara tepat ? Atau, dapatkah aktivitas membaca kita tidak mencapai makna-makna yang terkandung di dalam sebuah buku ? Atau, dapatkah aktivitas membaca kita gagal mendapatkan atau menghasilkan buah yang seharusnya muncul setelah kita membaca ? Hal ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana modus membaca kita. Erich Fromm menyebutkan dua modus dasar dalam pengalaman kita sehari-hari, memiliki (to have) dan menjadi atau mengada (to be). Aktivitas membaca dapat berjalan pada modus memiliki maupun menjadi.
Membaca dalam modus memiliki terkait dengan bagaimana kita sekedar menimbun cerita atau informasi, sekedar tahu akhir plot, siapa yang kalah siapa yang menang, siapa gagal siapa bahagia; sekedar mendapatkan ungkapan menarik, sekedar menaklukkan buku yangg tebal atau buku terkenal. Kita dapat menyebutnya sebagai membaca gaya bank (adaptasi dari pendidikan gaya bank-nya Freire). Membaca hanya sekedar untuk mendepositokan informasi atau pengetahuan untuk persiapan penarikan kembali suatu saat nanti. Penarikan kembali informasi, pengetahuan itu bisa terjadi saat ujian atau saat kita mulai berhasrat untuk membanjiri orang dengan informasi mengenai satu topik tertentu agar terlihat penuh wawasan.
Modus menjadi terkait dengan partisipasi internal, pemberian respon terhadap apa yang dibaca, memahami kerangka pikiran bacaan, mengetahui tidak untuk sekedar menimbun banyak pengetahuan. Descartes mengibaratkan membaca sebagai dialog dengan tokoh-tokoh besar. Membaca dalam modus menjadi merupakan sebuah dialog. Ada proses bertanya-jawab dalam membaca. Modus menjadi berusaha mengkaitkan bacaan dengan perubahan cara berpikir, bersikap dan berperilaku. Ada semacam transformasi batin di sana.
Peradaban Buku
Satu sisi yang juga bisa diberikan apresiasi dari budaya Ilmu dalam peradaban Islam adalah penggunaan medium buku sebagai sarana penyebaran pengetahuan di dunia Islam. Lembaga penulisan buku –waraq–, perdagangan buku, perpustakaan – baik pribadi maupun lembaga kenegaraan– , sangat berkembang di dunia Islam ketika itu. Sebagaimana juga munculnya lingkaran studi di mesjid-mesjid, diskusi ilmiah di istana-istana penguasa, atau munculnya lembaga-lembaga pengajaran dari tingkat dasar hingga univesitas (kulliyah). Sehingga tidak berlebihan jika Sardar menyebut juga kekhasan peradaban Islam dengan peradaban buku. Penyebaran buku melalui perdagangan juga sangat berkembang,. Di zaman klasik, setiap kota besar di dunia Islam memiliki bazar buku masing-masing (suq al waraqa). Aktivitas para pedagang buku tidak semata-mata menjualbelikan buku, tetapi toko-toko mereka juga berperan sebagai tempat-tempat diskusi. Sebuah karya indeks mengenai buku-buku di dunia Islam di masa itu, Al Fihrist, sebuah karya yang terkenal dikalangan sejarawan, ternyata dikarang oleh Ibn Nadim seorang pedagang buku..
Rujukan
[KT] Knowledge Triumpant, Franz Rosenthal. Brill, 2007
[KP] Konsep Pengetahuan Dalam Islam, Wan Mohd. Nor Wan Daud. Pustaka, 1997
[BI] Budaya Ilmu, Satu Penjelasan, Wan Mohd. Nor Wan Daud. Pustaka Nasional Singapura, 2003
[IPT] Ilmu dalam Perspekif Tasawuf, Al Ghazali, Karisma 1996 (Terjemahan Kitab Al ‘Ilm dari Ihya ‘Ulumuddin).Anwar Ibrahim. Renaisans Asia. Mizan. Bandung. 1998
Ziauddin Sardar. Wajah-Wajah Islam. Mizan. Bandung 1992
Ziauddin Sardar. Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim. Mizan. Bandung,1986.
Ziauddin Sardar. Masa Depan Islam. Pustaka.Bandung 1989.
Ziauddin Sardar. Merombak Pola Pikir Intelektual Muslim. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.2000
Yusuf Qaradhawi. Menghidupkan Nuansa Robbaniah dan Ilmiah. Pustaka Al Kautsar. Jakarta, 1996.
Yusuf Qaradhawi. Rasul dan Ilmu. Rosda Karya Bandung.1996
Pedersen. Fajar Intelektualisme Islam. Mizan. Bandung. 1996.
Franz Rosenthal. Etika Kesarjanaan Muslim, Dari Al Farabi hingga Ibn Khaldun. Mizan. Bandung. 1996.
Syed Hussein Alatas. Intelektual Masyarakat Berkembang. LP3ES. Jakarta. 1988.
Fukuzawa Yukichi. Jepang Di Antara Feodalisme dan Modernisme (terj. Encouragement of Learning). Panca Simpati. Jakarta. 1985