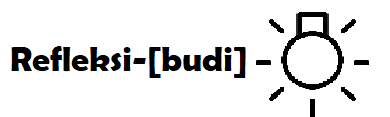Faktor pembeda filsafat modern dengan filsafat Islam, menurut Roger Geraudy adalah pada filsafat modern problem yang ingin dipecahkan adalah bagaimana pengetahuan itu mungkin, sedangkan pada filsafat Islam adalah bagaimana kenabian itu mungkin. Pada tulisan ini kita tidak akan meninjau kenabian sebagai masalah filsafat. Kita akan mencoba memahami kenabian dan wahyu dalam perspektif fenomenologi yang dikembangkan oleh Malik Bennabi.
Menurut Malik Bennabi fenomena keagamaan merupakan kenyataan antropologis dalam sejarah manusia. Manusia selalu bergulat dengan problem spiritual, metafisika dalam setiap periode sejarahnya. Dari suku sederhana di masa lampau dan modern, hingga peradaban-peradaban kuno dan modern, agama tetap merupakan fenomena dalam kehidupan mereka. Mengutip satu pernyataan sosiologis, Bennabi menegaskan bahwasanya manusia adalah makhluk religius (homo religious) dalam esensinya. Pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan yang didengungkan di era modern ini pada dasarnya adalah artifisial. Menurut Bennabi, pertentangan itu adalah antara dua agama; antara penjelasan materialistik dan penjelasan teistik terhadap problem-problem metafisika yang ada.
Karena agama adalah fenomena yang built-in dalam kehidupan manusia, kita menjumpai fenomena keagamaan ini dalam setiap fase kehidupan manusia dalam berbagai variasinya, baik politeisme maupun monoteisme. Monoteisme merupakan fenomena yang menjadi kunci selanjutnya dalam analisis Bennabi atas fenomena keberagamaan.
Fenomena monoteisme ini terkait dengan gerakan kenabian dan fenomena wahyu sebagai mediumnya. Basis utama dasar analisisnya adalah fakta fenomenologis dari kedua hal tersebut. Sebuah kejadian yang muncul sekali saja mungkin tidak memiliki signifikansi untuk diperhatikan guna diteliti lebih lanjut. Sebuah kejadian mendapatkan justifikasi kepentingannya dari perulangan yang terjadi. Kenabian dan Wahyu tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena kenabian dan wahyu tidak muncul hanya sekali sepanjang sejarah, tetapi ia terjadi berulang kali. Itulah sebabnya kenabian merupakan fenomena. Metodologi ini merupakan inspirasi yang didapat Bennabi dalam surat al Ahqaf ayat 9, “Katakanlah: Aku bukan pembawa pengajaran baru dari para rasul itu, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat dengan aku dan dengan kamu. Aku hanya menurut apa yang diwahyukan kepadaku.”
Untuk memahami Islam, berdasarkan fakta fenomenologis ini, kita dapat memahaminya dalam sorotan agama-agama monoteistik yang lebih dahulu. Karena Islam sendiri mengklaim sebagai kelanjutan dari risalah-risalah terdahulu. Dengan demikian klaim kebenaran Islam memiliki basisnya dalam kesamaan pesan dan kesamaan fenomena pembawa pesannya dengan agama-agama monoteis terdahulu. Sejak zaman Ibrahim, secara periodik muncul orang-orang yang membawa pesan kepada umatnya, pesan yang mereka dapatkan melalui komunikasi khusus yang disebut wahyu.
Karena fenomena agama monoteis terkait dengan fenomena kenabian maka perlu dipahami karakteristik dari fenomena tersebut sehingga dapat ditentukan standar utama dari klaim kenabian yang sebenarnya. Berdasar sifat dari karakter otoritatif dalam pesan kenabian, kita mendapati pengakuan kenabian dalam beberapa babakan sejarah Bani Israel kadang kala menjadi tren. Sehingga perlu dibedakan kenabian otentik dengan pengakuan kenabian semu (palsu) yang muncul.
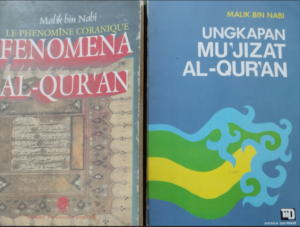 Tentu saja sebelumnya kita harus memastikan keotentikan sumber historis dari riwayat yang diterima. Berdasarkan pemikiran ini, Bennabi kemudian meneliti kasus Kenabian Jeremiah dalam kitab Perjanjian Lama dan mengkontraskannya dengan klaim-klaim palsu kenabian (pseudo-prophethood) yang disampaikan oleh mereka yang sejaman dengan Jeremiah. Pemilihan kasus Kenabian Jeremiah ini berdasarkan kenyataan sejarah bahwa dokumen sejarah [Kitab Jeremiah] berdasarkan studi biblikal dinyatakan sebagai satu-satunya dokumen yang paling otentik, sebagaimana dikutip oleh Bennabi.
Tentu saja sebelumnya kita harus memastikan keotentikan sumber historis dari riwayat yang diterima. Berdasarkan pemikiran ini, Bennabi kemudian meneliti kasus Kenabian Jeremiah dalam kitab Perjanjian Lama dan mengkontraskannya dengan klaim-klaim palsu kenabian (pseudo-prophethood) yang disampaikan oleh mereka yang sejaman dengan Jeremiah. Pemilihan kasus Kenabian Jeremiah ini berdasarkan kenyataan sejarah bahwa dokumen sejarah [Kitab Jeremiah] berdasarkan studi biblikal dinyatakan sebagai satu-satunya dokumen yang paling otentik, sebagaimana dikutip oleh Bennabi.
Terkait dengan fenomena kenabian atau wahyu ini kesaksian yang dapat kita gunakan secara unik adalah kesaksian Nabi itu sendiri. Uji validitas fenomena (kenabian) ini dilakukan melalui kesaksian Nabi itu sendiri dan kandungan pesan yang dia bawa.
Kesaksian seorang Nabi atas fenomena yang dia alami sendiri memberikan penerangan kepada kita akan munculnya pemisahan aku subjektif seorang Nabi dengan aku objektif yang tidak dapat menolak misi yang dia terima secara meyakinkan, sehingga ia dikuasai oleh panggilan (misi) tersebut dan menekan kemauan subjektifnya. Dalam ungkapan Jeremiah, ketika ia hendak berhenti dari melaksanakan tugas mengingatkan Bani Israel akan kehancuran yang menunggu mereka, hingga dia mendapatkan beragam hujatan atas apa yang dia dakwahkan, di hatinya muncul sesuatu seperti api yang bergolak, yang dia berusaha menghindarkan dirinya dari tugas itu, tapi tak dapat dilakukannya. Ada kekuatan yang menundukkan kehendak subjektifnya yang kemudian menentukan perilkau eksternalnya. Dari sini kita menemukan ciri pertama karakteristik fenomena kenabian ini yaitu, adanya faktor psikologis eksternal yang mengeliminasi faktor “aku” lainnya dalam keputusan akhir Nabi mengenai perilaku objektif yang ditunjukkannya. Dalam hal ini kita mendapati adanya faktor eksternal yang memaksa sang Nabi untuk menyampaikan pesannya.
Ciri kedua, yang diungkapkan oleh Bennabi, terkait fenomena kenabian ini berurusan dengan pesan yang bernilai paradoksal mengenai fakta-fakta masa depan, yang diajarkan oleh sesuatu yang absolut, tanpa basis logis dalam kejadian kontemporer. Ajaran atau pesan yang disampaikan mengandung unsur-unsur yang di luar nalar temporer untuk mengkonseptualisasikannya. Sedangkan pesan yang disampaikan oleh para nabi palsu yang banyak didapati pada masa Jeremiah, bersifat oportunis, mengikuti kemauan masyarakatnya; mereka memilih netral secara moral, dengan tetap menekankan klaim eksklusif keagamaan mereka. Hal ini berbeda dengan khutbah, dakwah menakutkan yang penuh ancaman, yang disampaikan Jeremiah, yang menubuatkan dominasi dan penguasaan asing serta kehancuran tempat ibadah mereka.
Selanjutnya, Bennabi mengungkapkan, fenomena seperti ini memiliki keserupaan internal dan eksternal yang secara kontinu yang kita dapati pada manifestasi kenabian di setiap zaman.
Berdasarkan kriteria tersebut, untuk menilai kasus Islam kita bisa menerapkan penilaian kriteria di atas terhadap Muhammad sebagai Nabi dan Al Quran sebagai pesan yang dibawa. Sebelum melakukan penilaian, sebuah catatan terkait dengan problem teks Quran dan Hadist sebagai sumber sejarah perlu ditegaskan. Quran sebagai dokumen religius merupakan satu-satunya sumber keagamaan yang otentisitasnya terjamin. Hadist sebagai sumber historis memiliki model pengujian yang luar biasa terstruktur sehingga memungkinkan pemilahannya berdasarkan tingkat otentisitasnya. Berikut ini merupakan hasil analisa Bennabi terhadap penerapan dua kriteria di atas, yang memberikan afirmasi positif terhadap posisi Muhammad SAW sebagai Nabi maupun pesan Al Qur’an sebagai pesan otentik Tuhan kepada manusia.
Pembawa Pesan : Muhammad SAW
Salah satu kunci untuk memahami kenabian Muhammad sebagai sebuah fenomena di luar kehendak dirinya, karena satu-satunya rujukan yang bisa kita nilai adalah keterangan dirinya maka kita harus mempertimbangkan keyakinan dirinya terhadap fenomena yang datang kepadanya (kenabian/wahyu). Kriteria untuk menilai keyakinan dirinya dapat dibagi menjadi kriteria fenomenal dan kriteria rasional.
Kriteria fenomenal terkait dengan bagaimana wahyu turun. Kriteria ini memberikan basis objektif bagi fenomena tersebut. Pertama-tama, fenomena ini muncul pada titik tertentu usia Muhammad SAW, yaitu saat ia berusia empat puluh tahun, pada rentang waktu sebelum wahyu itu muncul beliau merupakan sosok yang sudah memiliki kredibilitas moral yang tinggi dalam masyarakatnya. Setelah wahyu pertama itu turun berangsur-angsur selama kurang lebih dua puluh tahun. Ketika wahyu itu turun, biasanya selalu disertai dengan fakta-fakta fisiologis tertentu, kemunculan suara (mirip lonceng atau suara lebah), rasa berat yang memeluhkan tubuh; tetapi dalam kondisi kesadaran yang tinggi. Wahyu juga muncul di luar kehendak Muahammad, tidak mengikuti kemauan beliau waktu kehadirannya. Banyak riwayat mengungkapkan kadang berhari-hari beliau berharap wahyu hadir, tetapi tidak turun juga.
Kriteria rasional terkait bagaimana usaha yang dilakukan Muhammad untuk meyakinkan diri beliau terkait dengan fenomena yang dialaminya. Pernyataan beliau ketika wahyu pertama turun, dengan mengatakan “Aku tidak dapat membaca !” merupakan refleksi kesadaran peribadinya terhadap fenomena yang muncul di hadapannya. Konsultasi beliau dengan istrinya, Khadijah, mengenai fenomena yang dialaminya memberikan peluang baginya secara objektif menilai fenomena itu. Saat perintah “Wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan !” hadir, keyakinan dirinya terhadap fenomena yang di luar kehendaknya terekam pada kata-katanya yang beliau sampaikan kepada Khadijah, bahwa malaikat telah memeritahkannya untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Selanjutnya keyakinan pribadi ini dapat diafirmasi dalam kehidupan pribadinya, sejarah perjuangannya. Kisah penolakan beliau di hadapan paman beliau, Abu Thalib, ketika ditawarkan untuk menghentikan dakwah beliau dengan beragam tawaran cukup menjadi saksi keyakinan diri beliau ini. Pada sisi lain, kita juga mendapatkan fenomena yang disebut iltifat oleh para ahli ilmu Al Qur’an, yaitu fenomena perubahan kata ganti secara mendadak dalam satu ayat wahyu yang beliau terima. Di sini beliau (SAW), menyadari ketidakberwenangan beliau mengganti atau melakukan abrogasi (penghapusan) terhadap pesan yang telah beliau terima. Sisi lain terkait yang dapat kita perhatikan adalah sisi bagaimana secara objektif beliau menilai pesan kenabian yang beliau bawa ini, dimana beliau membedakan secara tegas mana yang merupakan wahyu dan mana yang merupakan pemikiran pribadi/subjektifnya. Kisah penyerbukan kurma yang gagal dapat dijadikan sebagi contoh, bagaimana beliau membedakan pesan wahyu dengan pendapat peribadi beliau.
Pesan : Al Qur’an
Karakteristik utama dari fenomena Quran adalah berangsur-angsurnya proses pewahyuannya dan unit kuantitatifnya. Keberangsuran pewahyuannya mengafirmasi keberulangan kejadiannya dalam rentang waktu dua puluh tiga tahun. Keberangsuran pewahyuan ini juga merupakan sarana pedagogis kelahiran sebuah agama dan pembentukan sebuah peradaban. Unit kuantitatif pewahyuan bervariasi dari satu ayat hingga satu surat. Pemeriksaan terhadap unit kuantitatif wahyu ketika diturunkan mengafirmasi kondisi “reseptivitas” Muhammad terhadap turunnya wahyu itu. Unit kuantitatif ini juga kadangkala membawa konsepsi yang sepenuhnya tidak dimengerti selama periode/ masa itu. Bennabi memberikan contoh satu ayat (ayat 23 surat ke-4/An Nisa) terkait bagaimana satu unit kuantitatif dalam wahyu (ayat) mengakomodasi beragam sudut pandang dan pertimbangan serta model komposisi yang mengesankan. Ayat ini secara rinci mendaftar mereka yang dilarang dikawini dalam urutan logis, dengan tingkat gradasi hubungan darah dan keturunan, demikian pula pengutamaan garis keturunan laki-laki atas garis hubungan perempuan (keponakan perempuan dari saudara laki-laki disebut lebih dulu daripada keponakan perempuan melalui saudara perempuan, garis darah melalui suami disebut dulu daripada garis darah melalui istri). Hal ini menujukkan kemustahilan proses komposisi manusiawi dalam waktu relatif singkat terjadi ketika ayat itu hadir.
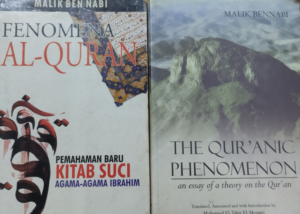 Demikian pula dengan aspek mukjizat sastranya, yang merupakan aspek tantangan yang dimunculkannya pada saat wahyu itu disampaikan. Bagi kita di zaman modern, yang terdidik secara modern dalam lingkungan Cartesian, ada banyak kesulitan tertentu untuk mengapresiasi aspek ini kecuali dengan perangkat ilmu bahasa yang perlu dikuasai. Tetapi dari sudut pandang bahasa secara umum kita mendapati bagaimana melalui Al Qur’an bahasa Arab bertransformasi dari tahap dialektik primitifnya ke bahasa yang ditata untuk memuat pemikiran dan peradaban baru. Bennabi menyebutkan bagaimana term-term asing diadaptasi dengan tetap menegaskan konsep monoteistik murninya, salah satunya adalah nama pembeli Yusuf dalam Bibel yang disebut Potiphar yang menurut ahli mengenai Mesir kuno berasal dari kata poti yang berarti yang disenangi dan phar yang berarti penasihat, kemudian kata itu berkonotasi sebagai dewa matahari yang disayangi. Al Qur’an menggunakan kata aziz yang memuat arti disenangi, disayangi dengan menghindari konotasi politeistiknya.
Demikian pula dengan aspek mukjizat sastranya, yang merupakan aspek tantangan yang dimunculkannya pada saat wahyu itu disampaikan. Bagi kita di zaman modern, yang terdidik secara modern dalam lingkungan Cartesian, ada banyak kesulitan tertentu untuk mengapresiasi aspek ini kecuali dengan perangkat ilmu bahasa yang perlu dikuasai. Tetapi dari sudut pandang bahasa secara umum kita mendapati bagaimana melalui Al Qur’an bahasa Arab bertransformasi dari tahap dialektik primitifnya ke bahasa yang ditata untuk memuat pemikiran dan peradaban baru. Bennabi menyebutkan bagaimana term-term asing diadaptasi dengan tetap menegaskan konsep monoteistik murninya, salah satunya adalah nama pembeli Yusuf dalam Bibel yang disebut Potiphar yang menurut ahli mengenai Mesir kuno berasal dari kata poti yang berarti yang disenangi dan phar yang berarti penasihat, kemudian kata itu berkonotasi sebagai dewa matahari yang disayangi. Al Qur’an menggunakan kata aziz yang memuat arti disenangi, disayangi dengan menghindari konotasi politeistiknya.
Karakteristik lain yang perlu diperhatikan adalah kesamaan antara pesan Bibel dan Al Qur’an, tetapi juga sekaligus perbedaannya. Kesamaan beberapa pokok pesannya terkait dengan masalah metafisika (ketuhanan), eskatologi (hari akhir), kosmologi, moralitas. Aspek metafisis pada Al Qur’an terutama menegaskan monoteisme yang murni dan jelas, rasional, ketat dan lebih spiritual; dibanding Bible (yang lebih berkonotasi nasionalis) maupun ajaran Kristen (yang memberikan status ilahiah kepada entitas manusia). Eskatologi Qur’an (kiamat, surga dan neraka, malaikat dan hal gaib lainnya) lebih jelas, detail, gamblang. Berbeda dengnan Perjanjian lama yang lebih banyak konsern pada pengorganisasian masyarakat, dan Perjanjian Baru yang menekankan kerajaan Allah dalam bentuk yang sangat abstrak. Jika Bible menekankan moralitas kelompok, sedangkan Injil menekankan moralitas individu, maka nilai moralitas Qur’an menekankan baik nilai moral individu maupun kelompok. Ganjaran individu akan diterima di akhirat nanti, sedangkan ganjaran kelompok akan diterima di dunia ini.
Bennabi mencoba mengkomparasikan kisah Yusuf dalam Quran dan Bible. Melalui analisa terhadap persamaan dan perbedaan yang muncul, serta akurasi kisah yang ada dalam Al Qur‘an, Bennabi menyimpulkan tidak mungkinnya sumber dan detail kisah itu (dengan segenap perbedaan yang sangat signifikan) didapatkan dari lingkungan sosial masyarakat arab ketika itu maupun proses belajar yang dilakukan oleh Muhammad SAW.
Lebih lanjut Bennabi menambahkan beberapa aspek yang mengafirmasi pesan Al Qur’an yang muncul di luar dari kecerdasan subjektif manusiawi Muhammad sang pembawa pesan maupun di luar lingkungan sosial budaya masyarakat Arab, sebagai tambahan bagi aspek-aspek psiko-skriptural yang telah dibahas di atas. Bennabi menyampaikan aspek antisipasi wahyu terhadap peristiwa yang dialami oleh Muhammad, seolah-olah sudah terencana sebelumnya. Demikian pula dengan aspek metafora yang digunakan Al Qur’an yang tidak hanya menggunakan metafora yang diambil dari lingkungan geografis arab saja, tetapi justru banyak yang diambil dari lingkungan yang di luar geografi arabia (misal laut atau tanam-tanaman yang dihidupkan oleh hujan). Aspek lain, kita dapat mempelajari lebih lanjut aspek-aspek koreksi terhadap pribadi Nabi dalam Quran terkait dengan peristiwa-peristiwa yang dialami (wahyu yang bertentangan dengan keputusan peribadi maupun koreksi terhadap keputusan yang sudah diambil). Hal lain yang juga perlu mendapat pertimbangan adalah antisipasi Quran terhadap fenomena ilmiah modern, yang saat ini dikenal sebagai aspek kemukjizatan ilmiah dalam Al Qur’an, seraya perlu diingat peringatan yang juga disampaikan Bennabi bahwa Al Qur’an bukanlah buku ilmiah, bukan buku ilmu pengetahuan alam.
Karya Pembanding
 Dalam pengantarnya untuk buku Bennabi ini, Muhammad Abdullah Draz (Dr. M.A. Draz, محمد عبد الله دراز) menyatakan rasa kegembiraannya dalam membaca karya Bennabi ini, sebagian disebabkan karena keyakinannya terhadap upaya penyelidikan serius seringkali menghantarkan pencari kebenaran yang saling independen pada kesimpulan yang identik atau serupa. Berdasarkan hal ini kita bisa memberikan perbandingan terhadap risalah Bennabi ini dengan risalah yang ditulis oleh Muhammad Abdullah Draz dalam karyanya An Naba’ Al Azhim [The Quran, An Eternal Challenge], juga karya disertasi pertamanya mengenai Pengantar Kepada Al Qur’an (Introduction to Qur’an). (Sebagai informasi, disertasi keduanya berbicara mengenai konsep Moral dalam Al Qur’an, dusturul akhlaq fil qur’an). Melalui dua risalah ini kita dapat melihat bagaiman beliau menangani problem yang identik dengan yang ditangani oleh risalah Bennabi, dan kemiripan metode mereka.
Dalam pengantarnya untuk buku Bennabi ini, Muhammad Abdullah Draz (Dr. M.A. Draz, محمد عبد الله دراز) menyatakan rasa kegembiraannya dalam membaca karya Bennabi ini, sebagian disebabkan karena keyakinannya terhadap upaya penyelidikan serius seringkali menghantarkan pencari kebenaran yang saling independen pada kesimpulan yang identik atau serupa. Berdasarkan hal ini kita bisa memberikan perbandingan terhadap risalah Bennabi ini dengan risalah yang ditulis oleh Muhammad Abdullah Draz dalam karyanya An Naba’ Al Azhim [The Quran, An Eternal Challenge], juga karya disertasi pertamanya mengenai Pengantar Kepada Al Qur’an (Introduction to Qur’an). (Sebagai informasi, disertasi keduanya berbicara mengenai konsep Moral dalam Al Qur’an, dusturul akhlaq fil qur’an). Melalui dua risalah ini kita dapat melihat bagaiman beliau menangani problem yang identik dengan yang ditangani oleh risalah Bennabi, dan kemiripan metode mereka.
Mengenai darimana sumber Al Qur’an, apakah ia karangan Muhammmad atau bukan, Dr. M.A. Draz dalam salah satu bukunya di atas memulai dengan mendiskusikan mengenai psikologi plagiat dan atribusi sebuah karya terhadap diri seseorang. Seorang plagiat tidak akan mengatribusikan sebuah karya besar kepada orang lain. Hal ini merupakan kontra dari apa yang terjadi terhadap Muhammad yang mengatribusikan apa yang dia terima [wahyu] kepada Tuhan. Dr. M.A. Draz juga mendiskusikan mengenai situasi turunnya wahyu yang diluar kehendak dirinya, koreksi wahyu terhadap apa yang dilakukannya, serta mengenai nubuat (prediksi-prediksi masa depan) Quran mengenai dakwah Muhammad (janji kemenangan yang diberikan justru pada saat kondisi sulit dialami), masa depan para penentang dakwah dan isu-isu tertentu (kemenangan tentara Bizantium atas Persia misalnya). Setelah menegaskan semua ini, Draz berusaha menjawab pertanyaan mengenai guru Muhammad, dengan menegaskan ketidakvalidan adanya guru personal yang mengajarkan wahyu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan muatan pesan Quran yang tidak bisa diafirmasi sebagai produk pemikiran manusia. Sehingga guru satu-satunya yang mungkin adalah guru yang ghaib, malaikat Jibril yang membawa pesan Allah SWT.
Apakah latar geografis arab dapat dijadikan titik tolak untuk menyatakan bahwa Al Qur’a merupakan produk lingkungan sosial itu ? Quran memberikan bagaimana gambaran tradisi dan perilaku yang dipraktekkan oleh paganis arab dan mengkritik serta mengutuknya; praktek mengubur anak perempuan, prostitusi, kaum wanita sebagai warisan, penindasan yatim, pengabaian orang miskin dan penindasan yang lemah. Semua ini merupakan manifestasi dari kebodohon, jahiliyah. Secara ajaran, pagan arab penuh dengan superstisi dan takhayul. Memang didapati ada orang hanif yang berdiri berbeda dengan tradisi mereka, tetapi mereka mengakui tidak memiliki kebenaran yang bisa dipegangi dan praktek ibadah yang sesuai bagi keyakinan mereka itu.
Apakah Al Qur’an bersumber dari pengaruh Judeo Kristian ? Secara praktis, praktek keagamaan Judeo Kristian tidak memberikan pengaruh besar; bahkan ada ungkapan pengaruh mereka hanya pada tersebarnya minuman keras. Secar intelektual juga, tidak ada terjemahan taurat dan injil dalam bahasa arab ketika itu, penguasaan teoritis agama-agama ini terbatas pada kalangan intelektual mereka (rahib) saja. Lingkungan arab sendiri adalah lingkungan buta baca-tulis. Nabi SAW juga adalah nabi yang ummi.
Untuk mengerti mengenai ajaran atau pesan Qur’an, M.A. Draz menyatakan kita dapat melakukan studi terhadap Al Qur’an dengan dua pendekatan, melalui pendekatan bahasa atau melalui pendekatan ide. Pendekatan secara artistik, lingustik dan retorika mengasumsikan pengetahuan yang mendalam dalam bahasa arab. Jika menggunakan pendekatan kedua, kita dapat memetakan ajaran Al Qur’an ke dalam tiga ide dasar; ide mengenai kebenaran, ide mengenai kebaikan dan ide mengenai keindahan.
Kebenaran relijius merupakan jawaban terhadap beragam pertanyaan mengenai hakikat besar yang menjadi pertanyaan filosofis yang memecah belah manusia. Pertanyaan mengenai, dari mana asal muasal alam semesta ? dan kemana semesta ini mengarah ? Ajaran yang diajarkan para utusan Allah haruslah ajaran yang sama. Satu ajaran ini berlaku bagi seluruh manusia (pada masa lalu maupun mendatang), manusia adalah satu umat, Tuhan adalah satu. Islam mengajak untuk kembali pada doktrin primordial itu.
Manusia tidak hanya memerlukan kepercayaan saja, tetapi juga memerlukan aturan hidup yang praktis, yang dapat mengarahkan aktivitasnya dari momen ke momen, dalam perilaku personalnya, dalam interaksinya dengan yang lain, juga dengan Tuhan. Manusia perlu iman, tetapi juga amal saleh, kepercayaan juga pengorbanan, orang beriman juga orang yang bermoral. Dogma dan hukum, kepercayaan dan kepatuhan. Semua rasul membawa skala keadilan dan menerima perintah untuk hidup secara terhormat, menyembah Tuhan dan mempraktekan keutamaan. Perhatikan 9 perintah Tuhan (dalam konteks ini sering dikenal sebagai sepuluh perintah Tuhan, di sini dengan mengecualikan perintah terkait hari sabat) dalam Taurat dan Quran. Demikian pula dengan ajaran-ajaran lain yang masih dapat kita temukan dalam Taurat atau Injil memiliki paralel yang sama dalam Quran.
Sebagai ilustrasi beliau menggambarkan mengenai hukum perceraian dan hukum kisas (balas) dan bagaimana posisi Al Qur’an. Taurat memberikan kebebasan penuh bagi suami untuk menceraikan istri, jika menemukan sesuatu aib terhadapnya. Injil mendukung hubungan suami-istri yang tidak terpisahkan, kecuali dalam kasus ketidaksetiaan. Dalam kasus hukum kisas, Taurat menuntut darah balas darah, sedangkan Injil menganjurkan pemaafan. Secara sekilas kita seakan akan melihat Injil membatalkan hukum taurat. Tetapi, dalam hal ini kita melihat hal ini merupakan dua aspek atau derajat dari hukum abadi yang sama; satu pada kutub keadilan, yang lain pada kutub kasih sayang. Moralitas berosilasi antara dua limit ini. Quran memberikan formulasi finalnya dalam 16:126, 4:20-21, 4:128, 4:35, 2:228-30, 65:12; Quran merekonsiliasi dua kutub ini, tetapi tidak berhenti di sini (demikian juga terhadap ajara-ajaran moralitas yang diwarisinya); Quran selain menjaga dan merekonsiliasi juga memiliki misi, untuk menyempurnakan, menyelesaikan ajaran-ajaran para nabi sebelumnya.
Terkait dengan aspek moralitas ini, Dr. M.A Draz menambahkan hal-hal baru yang muncul seiring dengan munculnya ajaran Al Qur’an, mengenai keutamaan personal (mengenai niat sebagai fondasi moralitas individu), mengenai kebaikan interpersonal (aturan kesopanan dan kesantunan), kebaikan kolektif dan universal (prinsip keadilan bagi semua), serta kebaikan internasional (prinsip perjanjian maupun kemungkinan perang yang legitimate).
Mengenai aspek keindahan dalam Al Qur’an, Dr. M.A Draz memberikan satu contoh (dari beragam sampel yang beliau sampaikan mengenai aspek ini), yaitu aspek koherensi satu surat dalam Al Qur’an. Menurut beliau tanpa memahaminya orang akan terjebak kepada prasangka tentang tema yang kacau, tanpa bentuk dalam ide, dan tanpa logika; yang diarahkan kepada Quran. Bagi beliau, jika ingin melihat keindahan sebuah desain, seseorang tidak cukup hanya melihat sebagian kecil ayat saja yang ditarik keluar dari konteksnya. Perlu sebuah visi menyeluruh atas sebuah surah, dari beragam sudut pandang; dengan demikian dia dapat melihat simetri antar bagian-bagiannya dan harmoni komposisinya. Beliau menemukan bahwa sebuah surat sangat teroganisasi, terdiri atas pendahuluan, pengembangan dan penutup. Pada permulaan beberapa ayat memberikan indikasi tema-tema yang akan dibahas. Urutan pengembangan sedemikian rupa sehingga setiap bagian tidak mengganggu bagian selanjutnya; setiap bagian menemukan tempatnya yang definit dalam sebuah koordinat. Akhirnya muncul kesimpulan yang berkorespondensi dengan pengantar/pendahuluan.
Jika kita mengambil fakta bahwa pewahyuan mengambil posisi (pada sebagian besarnya) sebagai responsi terhadap situasi tertentu, kita akan mendapatkan betapa ajaibnya penempatan ayat-ayatnya dalam sebuah surah. Kita bertemu fakta bahwa Quran tidak disusun secara kronologis. Tentu sudah ada rencana agung dalam penempatan ayat-ayatnya (sebuah aspek mukjizat). Beliau menyimpulkan, semua ayat dalam Quran dikembangkan berdasarkan perencanaan edukatif dan legislatif yang detail, dari awal hingga akhirnya oleh Allah. Teks yang sama, yang secara kronologis membentuk perencanaan edukatif yang sempurna, kemudian ditarik keluar dari urutan historisnya untuk kemudian dikelompokkan dan dialokasikan kedalam beragam framework dengan ukuran yang berbeda; dan dari sini penyebaran bentuknya yang (sudah ditentukan) muncul, guna dibaca dan dikomposisi dalam bentuk yang integral, dengan memiliki kohesi sastrawi secara logis yang tidak kalah sempurna dengan argumen logisnya; pada dua bentuk penataan ini kita memahami skema yang muncul bukan dari nalar manusia.
Melalui pemaparan dua risalah yang ditulis oleh Dr. M.A Draz di atas, pada dasarnya kita melihat metodologi yang serupa dengan risalah Fenomena Quran-nya Bennabi, dalam menganalisis basis bagi kebenaran Quran, yaitu dengan pemahaman yang jelas mengenai pribadi penerima wahyu [Muhammad] dan studi mendalam mengenai pesan yang diterimanya [Quran].
Rujukan
Fenomena Al Qur’an, Malik bin Nabi, PT Al Ma’arif. Bandung. 1983 [Terj. Azzhahirah Quraniyah].
Fenomena Al Qur’an, Pemahaman Baru Kitab Suci Agama-Agama Ibrahim. Malik Ben Nabi. Penerbit Marja’. Jakarta.2002. [Terjemahan dari The Quranic Phenomenon, 1983].
The Qur’anic Phenomenon, an essay of a theory on the Qur’an. Malik Bennabi. Islamic Book Trust. Kuala Lumpur. 2001.
The Quran : An Eternal Challenge. Muhammad Abdullah Draz. The Islamic Foundation. United Kingdom. 2001.
Asal-Usul Islam, dalam Islam Jalan Lurus diedit oleh Kenneth Morgan, (Judul asli Islam The Straight Path).