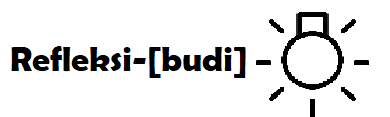Judul di atas memang memiliki kedekatan ide dengan tulisan Huntington pada awal era 90-an lalu, “The Clash of Civilization” (benturan antar peradaban). Tetapi isu yang akan diangkat adalah problem pemikiran dan ide. Kata “benturan” sendiri harus dimaknai dengan persaingan, perlombaan untuk membuktikan kebenaran ide dan usaha mencari manusia-manusia yang siap meyakini ide itu.
Krisis dan Kelahiran Ide
Krisis ekonomi yang terjadi hingga saat ini telah memberikan dampak perubahan terhadap tata kehidupan sosial-ekonomi-politik kita. Kesadaran terhadap krisis tersebut telah menstimulasi para intelektual untuk membongkar sebab-sebab problem yang melilit bangsa ini. Problem yang dihadapi bangsa dalam masa ini telah menyentak kesadaran banyak orang untuk mempertanyakan kembali “kebenaran” atau kelayakan gagasan terdahulu untuk menyelesaikan problem, maupun memberi arah yang tepat bagi kehidupan bangsa ini. Muncullah diagnosa-diagnosa dan alternatif pemecahan terhadap problem bangsa ini.
Maka, pertanyaan, diagnosa, dan alternatif gagasan baru banyak yang “lahir”. Kehidupan intelektual kini menemukan momentumnya. Problem yang ada pada tubuh bangsa masih begitu kompleks untuk terpecahkan. Sulit menyatakan problem itu dapat terjamah keseluruhannya oleh pikiran satu orang.
Dapat disimpulkan secara sederhana, kesadaran terhadap krisis yang ada saat ini — dengan rentang problem yang begitu luas — telah memberi ruang yang begitu besar untuk lahirnya gagasan-gagasan baru. Rentang problem yang luas dan begitu beragam juga menstimulasi pertanyaan-pertanyaan mengenai akar semua problem itu. Pada tahap ini gagasan-gagasan yang tumbuh tidak lagi bersifat praktis semata tetapi juga filosofis-ideologis.
Namun, tentu saja, lahirnya gagasan-gagasan tidak selalu distimulasi oleh kesadaran terhadap krisis dalam skala bangsa. Yang jelas ada catatan khusus, terbentuknya ruang yang besar ini secara tidak langsung juga menstimulasi “penzhahiran” ide-ide yang sebelumnya bergerak di bawah tanah. Dan, perguruan tinggi, sebagai institusi ilmiah, merupakan tempat yang subur bagi berkembangnya gagasan-gagasan tersebut. Gagasan yang saling bergerak membentuk sebuah dunia khusus, memiliki kekhasan dalam dinamika mereka. Namun, sebuah pemikiran yang tidak menyentuh akar kemasyarakatannya akan mengalami keterasingan, dan tidak akan menggerakkan manusia.
Logika Aktualitas
Keragaman gagasan –praktis atau filosofis-ideologis — merupakan kenyataan tanggapan terhadap problem bangsa ini. Dalam pluralitas ini, kaidah yang mengatur hidupnya sebuah gagasan dalam sebuah masyarakat adalah seperti yang dinyatakan oleh Malik Bin Nabi : logika aktualitas. Yaitu gagasan mana yang dapat memberikan diagnosa yang memuaskan secara intelektual, yang memberikan keyakinan untuk menyelesaikan problem, yang memberi ruang kemungkinan untuk ‘terjadi’, yang memberikan rasa keberdayaan untuk mengimplementasikannya. Seperti itulah gagasan yang akan menemukan latar untuk hidup dalam pemikiran masyarakat.
Dengan logika seperti ini pula kita dapat memahami pertumbuhan sebuah pergerakan. Pergerakan hanya akan dibangun oleh mereka yang telah memiliki kepuasan intelektual maupun moral terhadap gagasan-gagasan yang menjadi keyakinannya. Sebuah gagasan akan menjelma menjadi sebuah gerakan untuk membenahi problem yang ada, dengan keyakinan metodologis yang dimiliki oleh gagasan tersebut.
Kenyataan lain akan mengatakan adanya proses menebarkan gagasan itu ke semua orang. Karena gagasan yang hanya ‘mengumpul’ dalam diri seorang semata tidak memiliki efektifitas untuk ‘menjadi’. Pada proses mencari pendukung ini proses ‘meyakinkan’ terjadi. Pada titik ini pula persaingan antargagasan merupakan fenomena yang menggejala.
Tantangan Da’wah
Da’wah Islam kita dihadapkan oleh kenyataan seperti di atas, terlebih dalam kultur intelektual seperti perguruan tinggi. Fikroh Islam bukanlah pengecualian dari kaidah aktualitas. Ketika fikroh ini tidak lagi memiliki kedekatan dengan problem masyarakat, dan formulasi yang kita berikan tidak memuaskan, maka masyarakat pun akan menjauh dari fikroh Islam. Barangkali fenomena enggannya masyarakat, termasuk mahasiswa memenuhi undangan ke majelis-majelis da’wah perlu dicermati.
Namun yang dibutuhkan bukanlah penafsiran-penafsiran baru terhadap Islam, tetapi penyegaran kembali fikroh Islam yang orisinal. Karena inti dari pembaharuan Islam adalah kembali kepada asholah (orisinalitas), bukan menghidupkan Islam dalam sorotan ide-ide lain. Merupakan kecerobohan untuk memberi tafsiran Marxis terhadap Islam. Dan adalah reduksionis jika kita mengeliminasi beberap ajaran Islam agar Islam diterima dalam wajah yang lebih ‘kasih’. Hal yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita memformulasikan fikroh ini dalam tataran praktis maupun konsepsi yang tegar. Kebutuhan kita adalah bagaimana formulasi fikroh dalam tataran sikap dan kebijakan –dalam lini manapun selama terkait dengan objek da’wah — memenuhi kaidah ‘terpahami’ oleh masyarakat. Jelas, hal ini memerlukan perjuangan intelektual. Mengisi lini-lini da’wah intelektual, dalam suasana pertarungan ide seperti ini, merupakan kebutuhan mendesak.
Signifikansi ini juga akan sangat terasa dalam usaha mempersiapkan kader-kader da’wah dan menjaga kader da’wah yang ada. Stimagtisasi buruk terhadap da’wah sebagai tidak dialogis, doktriner, barangkali memiliki sebab pada sikap enggan menghadapi benturan ini. Sehingga kompensasi yang dilakukan adalah pada kegiatan-kegiatan yang memberikan rasa aman, dengan suasana homogenitas fikroh. Runutan lebih jauh mungkin membawa pada fenomena struktur kognisi kita terhadap fikroh Islam yang ‘tanggung’. Dalam makna menggantung antara tahu yang terpuaskan secara intelektual dan ketidaktahuan orang awam. Hal ini merupakan problem pendidikan. Suasana ‘tanggung’ ini juga menjelaskan fenomena berjatuhannya aktivitas da’wah karena godaan-godaan pemikiran yang tidak seirama dengan fikroh Islam.
Dalam tinjauan sejarah dapat kita fahami bahwa ketika pertama kali da’wah digulirkan Rasulullah, masyarakat memahami secara jelas tentang Islam. Sehingga mereka menolak bukan karena ketidakfahaman tetapi karena keengganan. Dan, mereka yang menerima, memerima dengan kepuasan dan keistiqamahan.
[Dimuat dalam Tarbawi edisi 14 Th. 2 30 November 2000 M/ 29 Sya’ba 1421 H, dengan sedikit editing, pembuangan kata “dan” dan “maka” yang bermula di awal kalimat. Saat ini Majalah Tarbawi sudah terbit lagi].